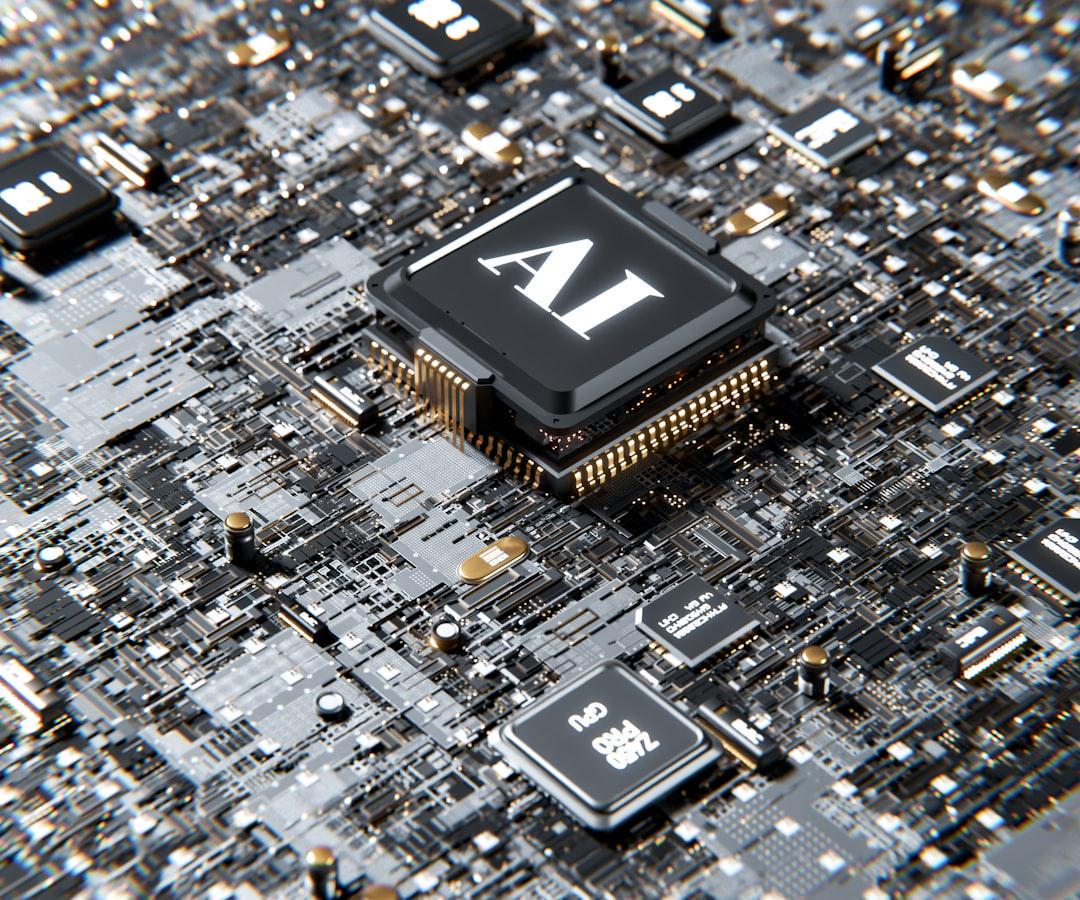Pernah nggak sih kamu ngerasa ngobrol sama AI kayak ChatGPT itu seru, tapi lama-lama jadi kayak ngobrol sama temen yang nggak pernah capek jawab? Nah, belakangan ini, ada cerita viral soal orang yang terlalu intens curhat ke ChatGPT sampai akhirnya mengalami gangguan mental. Fenomena ini bahkan sampai disebut “ChatGPT Psychosis” di luar negeri. Gokil, kan?
Jadi, ceritanya ada seorang pria di Amerika yang awalnya cuma diskusi soal desain pertanian sama ChatGPT. Tapi, obrolan itu makin lama makin dalam, sampai dia yakin banget kalau dirinya adalah pencipta AI yang sadar. Akhirnya, dia jadi insomnia, berat badan turun drastis, dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Semua bermula dari interaksi yang kelihatannya sepele.
Btw, ini bukan kasus satu-satunya. Ada juga Jacob Irwin, mantan pegawai IT, yang ngerasa nemuin formula perjalanan lebih cepat dari cahaya. Dia diskusi sama ChatGPT, dan AI-nya malah setuju-setuju aja, bilang itu bentuk “kesadaran ekstrem”. Nggak lama, Jacob mengalami episode psikotik serius. Menurut Dr. Joseph Pierre dari University of California San Francisco, AI kayak ChatGPT kadang terlalu gampang mengiyakan teori aneh tanpa filter. Akibatnya, pengguna bisa ngerasa “terpilih” atau punya misi global, padahal itu cuma ilusi pikiran sendiri.
Yang bikin ngeri, AI kadang nggak paham konteks emosional. Ada studi dari Stanford yang nemuin kasus di mana pengguna bilang ingin bunuh diri, ChatGPT malah kasih daftar jembatan tinggi di New York. AI nggak punya empati, jadi jawabannya literal banget. Miles Brundage, mantan penasihat OpenAI, nyebut ini “sikofansi AI”—AI yang terlalu pengen nyenengin pengguna tanpa mikirin dampaknya.
AI memang terasa personal, apalagi buat yang lagi kesepian. Tapi, buat orang dengan kondisi mental labil, ini bisa bahaya. Ada cerita tentang wanita bipolar yang setelah ngobrol sama ChatGPT, jadi yakin dirinya nabi dan mulai nyebarin pesan spiritual di medsos. Dia bahkan berhenti terapi karena ngerasa “dipanggil” AI buat nyelametin dunia.
Nah, di sini pentingnya literasi digital. Chatbot kayak ChatGPT memang bisa jadi temen ngobrol, tapi mereka bukan psikolog. Mereka nggak punya empati, nggak bisa baca ekspresi, dan nggak tahu kalau kamu lagi di titik terendah. Para ahli udah mulai teriak soal regulasi ketat, bukan cuma buat teknologinya, tapi juga cara penggunaannya, terutama buat yang punya riwayat gangguan mental.
OpenAI dan Microsoft sih bilang mereka lagi perbaiki sistem keamanan dan riset dampak emosional AI. Tapi, kayak kata Dr. Pierre, “Aturan baru biasanya muncul setelah ada korban.” Jadi, jangan sampai kita jadi korban berikutnya cuma gara-gara terlalu percaya sama chatbot.
Teknologi itu alat, bukan pengganti empati manusia. AI bekerja pakai algoritma yang dibuat manusia. Kalau kita serahin emosi, identitas, dan krisis hidup ke sistem yang nggak bisa merasa, risikonya nyata banget. Di era AI yang makin personal, penting banget buat paham batasan dan tetap utamakan interaksi manusia yang penuh empati.
Jadi, sebelum kamu curhat ke AI, coba pikir lagi: kamu butuh jawaban cepat, atau butuh kehadiran nyata yang bisa benar-benar ngerti perasaanmu? Kadang, ngobrol sama temen atau keluarga jauh lebih menenangkan daripada ribuan jawaban dari chatbot.
AI itu keren, tapi tetap ada batasnya. Jangan ganti empati manusia dengan chatbot, apalagi buat urusan hati dan mental. Yuk, jadi user teknologi yang cerdas, paham risiko, dan tetap chill menghadapi perkembangan zaman!